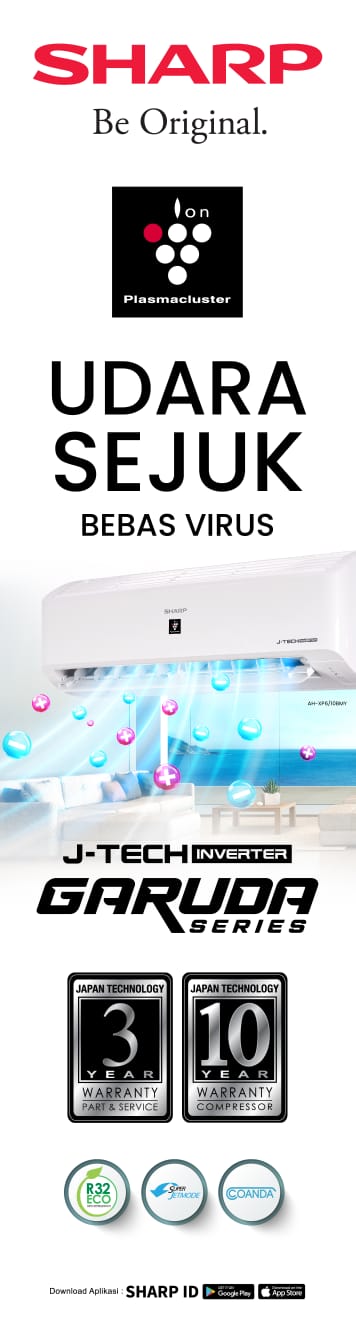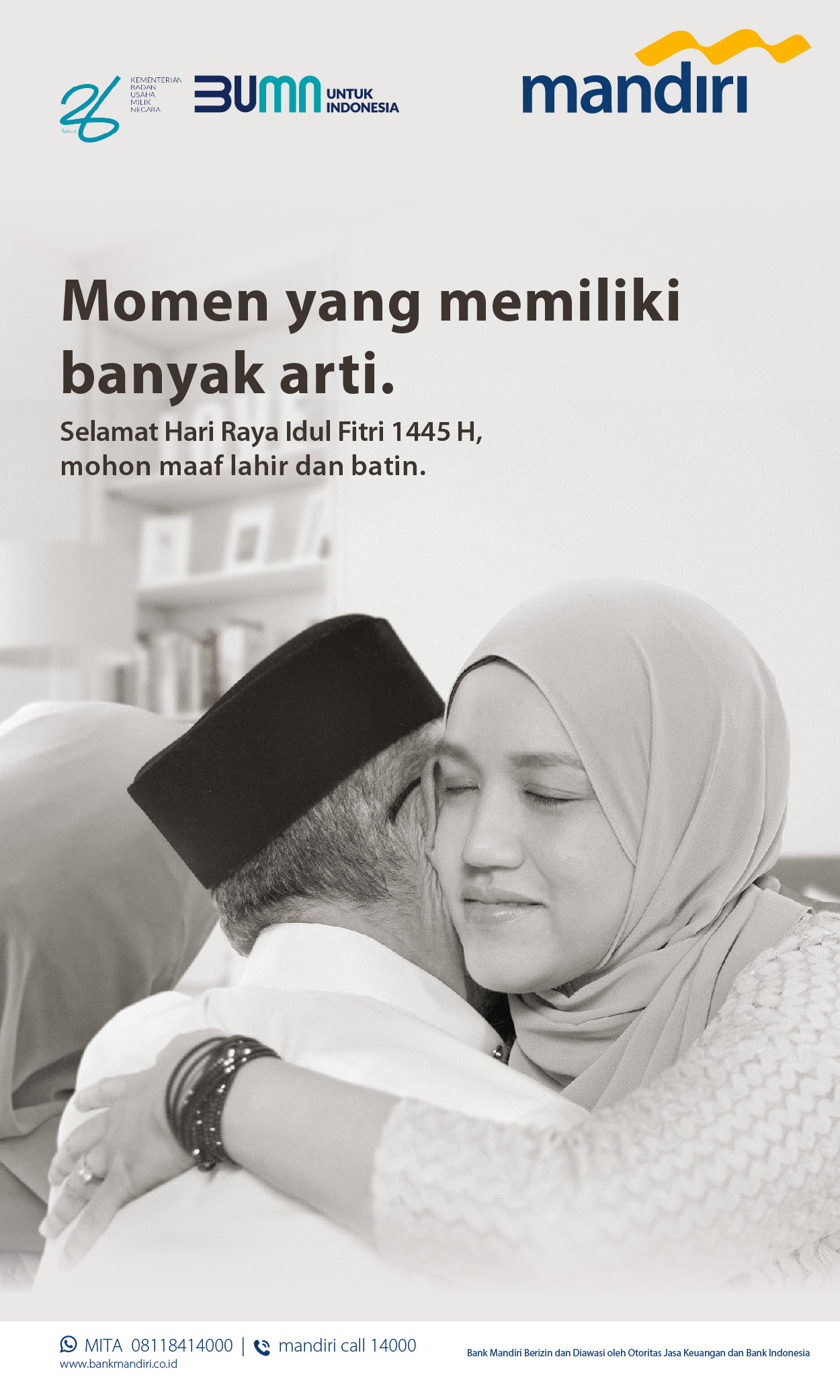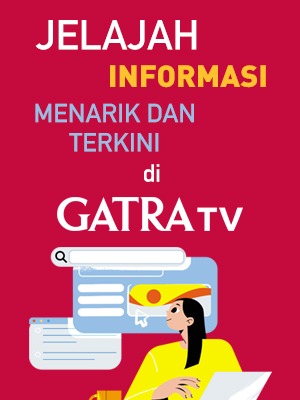Jakarta, gatra.net - Penghapusan syarat adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pemberian vaksin COVID-1, mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Terbitnya Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lain yang Belum Memiliki NIK membuat akses vaksin terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia.
Namun, tantangan tak berhenti hanya pada penghapusan persyaratan administrasi NIK. Harus ada langkah lanjutan untuk menerjemahkan berbagai aturan, yakni dengan menetapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang terpadu dan meliputi berbagai tahapan vaksinasi.
Tanpa juknis dan juklak yang terpadu, surat edaran itu berisiko menjadi kertas kosong yang tak ampuh menjawab tantangan akses vaksinasi bagi masyarakat adat, disabilitas, dan kelompok rentan lain.
Juknis diharapkan bisa melampaui persoalan administrasi NIK. Kerja sama antarlembaga pemerintah, baik pusat dan daerah, juga antar instansi di daerah, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga berbagai lembaga yang memiliki stok vaksin, sangat dibutuhkan agar masyarakat adat dan kelompok rentan bisa benar-benar mendapatkan vaksin.
Juknis dan juklak diharapkan mencakup berbagai tahapan program vaksinasi, yakni: metode sosialisasi dan informasi yang inklusif, pelaksanaan pre-screening yang memadai, pelibatan tokoh-tokoh lokal, penggunaan bahasa daerah, hingga pendampingan pasca vaksinasi.
Menurut Risna Utami, pendiri Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), sejauh ini peraturan penyelenggaraan vaksinasi masih bersifat umum dan belum dipahami penuh oleh pemerintah daerah. Pemilihan lokasi vaksinasi, misalnya, harus mempertimbangkan faktor bisa diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dan ini membutuhkan koordinasi antar lembaga.
“Kurangnya koordinasi di lapangan membuat pelaksanaan vaksinasi belum maksimal,” kata Risna. Kerap kali lokasi vaksinasi terlalu jauh atau berada di gedung yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas.
Koordinasi di lapangan juga perlu untuk memastikan pendataan penduduk bisa berjalan lancar. Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin menilai, Surat Edaran Kemenkes itu perlu didukung kepastian kehadiran petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat saat proses vaksinasi. Kehadiran petugas Dukcapil saat pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan sekaligus sebagai sarana pendataan penduduk.
Namun, jika Dukcapil tak bisa ikut hadir, menurut Hamid, maka perlu ada kesepakatan bentuk format data kependudukan yang mesti diambil oleh petugas vaksinasi. “Sehingga data yang dikumpulkan pelaksana vaksinasi sesuai dengan kebutuhan Dukcapil dan bisa digunakan untuk pelayanan penduduk,” kata Hamid.
Karena isinya masih bersifat umum, Surat Edaran Kemenkes itu juga bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap pemerintah daerah yang menjadi pelaksana vaksinasi di daerah. Pemerintah daerah akan menjalankan vaksinasi semampunya, yang boleh jadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan kelompok disabilitas. Menyamaratakan standar prosedur vaksinasi bagi semua warga sama saja dengan mengecualikan masyarakat yang selama ini cenderung tersisih.
Masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain perlu pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan berbeda ini tidak hanya dibutuhkan saat vaksinasi tetapi bahkan perlu dilakukan sejak tahap sosialisasi. Masyarakat adat dan kelompok rentan belum tentu sudah terpapar atau tidak bisa mengakses informasi terkait COVID-19.
Maulani A Rotinsulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menjelaskan, selama ini kaum disabilitas terpinggirkan. Akses dan layanan kesehatan untuk kelompok disabilitas relatif terbatas. Kalangan disabilitas belum tentu bisa mengakses informasi tentang COVID-19 dan vaksinasi secara memadai. Bagi disabilitas rungu, misalnya, informasi yang tersedia kerap tidak disertai teks atau penerjemah bahasa isyarat. Salah satu ekses yang timbul adalah banyaknya penyandang disabilitas yang kurang siap atau takut mendapat vaksin.
Menurut Maulani, terbatasnya akses kesehatan bagi penyandang disabilitas adalah persoalan yang telah berlangsung lama. Sebagian penyandang disabilitas hampir tak pernah mengecek kesehatan secara rutin. Akibatnya, mereka tidak memahami kondisi tubuh dan apakah ada penyakit ikutan (komorbid) yang perlu diperhatikan sebelum vaksinasi. “Karena itu, perlu pemeriksaan kesehatan sebelum vaksin (pre-screening) yang lebih detail,” kata Maulani menjelaskan.
Penyandang disabilitas juga membutuhkan fasilitas tambahan seperti konsultan kesehatan dan penerjemah bahasa isyarat. Perlu penerjemah untuk melancarkan komunikasi tenaga kesehatan dengan penyandang disabilitas. Jika tak ada penerjemah, maka harus diupayakan modifikasi cara penyampaian informasi. Misalnya penggunaan teks dalam komunikasi atau menggunakan masker transparan. “Agar disabilitas rungu bisa membaca gerak bibir tenaga kesehatan,” kata Maulani.
Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), memandang bahwa Surat Edaran Kemenkes itu baru langkah awal. Langkah penentu yang perlu dan wajib dibangun adalah sosialisasi, yakni memberi pemahaman, penentuan lokasi, dan pre-screening bagi masyarakat adat. Langkah sosialisasi ini perlu menggandeng tokoh-tokoh adat. Peran warga membantu warga selama pandemi telah terbukti menjadi pilar penting. Karenanya, partisipasi warga dan perhatian pada budaya lokal tak boleh diabaikan.
Salah satu cara sosialisasi, Rukka menekankan, adalah dengan menggunakan bahasa daerah. “Supaya informasi mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat adat. Agar masyarakat tahu kenapa vaksinasi ini benar-benar penting,” kata Rukka.
Sebagian besar masyarakat adat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Karenanya, layanan pre-screening yang lebih detail juga perlu diberikan kepada masyarakat adat. Pemeriksaan yang lebih komprehensif perlu dilakukan agar bisa diketahui status kesehatan dan adanya komorbid sebelum vaksinasi.
Petugas di puskesmas desa, puskesmas pembantu, dan para dokter yang diterjunkan untuk program vaksinasi perlu memeriksa masyarakat adat lebih dari sekadar memeriksa tekanan darah dan denyut nadi.
Lokasi pemeriksaan juga bisa digelar di balai adat. Sebab banyak masyarakat adat yang lebih akrab dengan kegiatan di balai adat, dari pada kegiatan yang digelar di fasilitas negara. “Pemeriksaan kesehatan perlu lebih komprehensif,” kata Rukka.
Selain pre-screening, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan perlu mendapatkan pendampingan usai diberi vaksin. Langkah ini dilakukan, agar mereka paham dan tak perlu panik jika terjadi efek pascavaksinasi atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Pendampingan ini perlu dilakukan agar jika ada efek samping dari vaksin, maka kejadian tersebut tidak berkembang menjadi hoaks. Keseluruhan program vaksinasi dalam upaya penanganan pandemi bisa berantakan jika terus-menerus dikikis hoaks.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menuntut Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan juknis dan juklak vaksinasi terpadu bagi masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain. Petunjuk teknis ini bisa menjadi standar bagaimana Pemerintah Daerah menggelar vaksinasi.
Koalisi merekomendasikan perlunya juknis dan juklak terpadu dalam pelaksanaan vaksinasi, yang meliputi:
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) perlu menjalin koordinasi erat dengan para penyelenggara vaksinasi. Agar pendataan penduduk, beserta data vaksinasi, bisa berlangsung dengan efisien, sehingga warga bisa langsung mendapatkan vaksin sekaligus masuk dalam data kependudukan.
2. Jika dari Dukcapil tak bisa mendampingi proses vaksinasi, maka perlu kesepakatan seperti apa format pendataan penduduk bagi penerima vaksin. Dengan demikian, data yang dikumpulkan pelaksana vaksinasi sesuai dengan kebutuhan Dukcapil dan bisa digunakan untuk kebutuhan selanjutnya.
3. Perlunya sosialisasi tentang vaksinasi yang menggandeng tokoh setempat, agar informasi mudah dipahami dan diterima warga. Sosialisasi juga perlu perlu dilengkapi dengan teks atau penerjemah informasi, sehingga informasi bisa diakses penyandang disabilitas. Informasi yang benar bisa mengurangi hoaks dan menambah keyakinan warga untuk ikut vaksinasi.
4. Perlu koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil agar pelaksanaan vaksinasi bisa menjangkau masyarakat adat dan mudah diakses bagi kalangan disabilitas. Baik itu untuk memilih lokasi vaksinasi hingga pemenuhan kebutuhan penerjemah bahasa isyarat.
5. Perlunya pre-screening yang lebih detail bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lain. Langkah ini dibutuhkan karena selama ini akses pemeriksaan kesehatan amat terbatas sehingga masyarakat adat dan kelompok disabilitas paham dengan kondisi kesehatan tubuh mereka sendiri.
6. Perlunya pendampingan pascavaksinasi untuk mengantisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) bagi masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain. Dengan pendampingan, kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi bisa segera diatasi dan tidak berkembang menjadi hoaks yang berisiko membahayakan program vaksinasi.



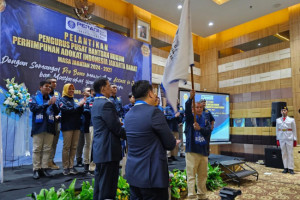

_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)