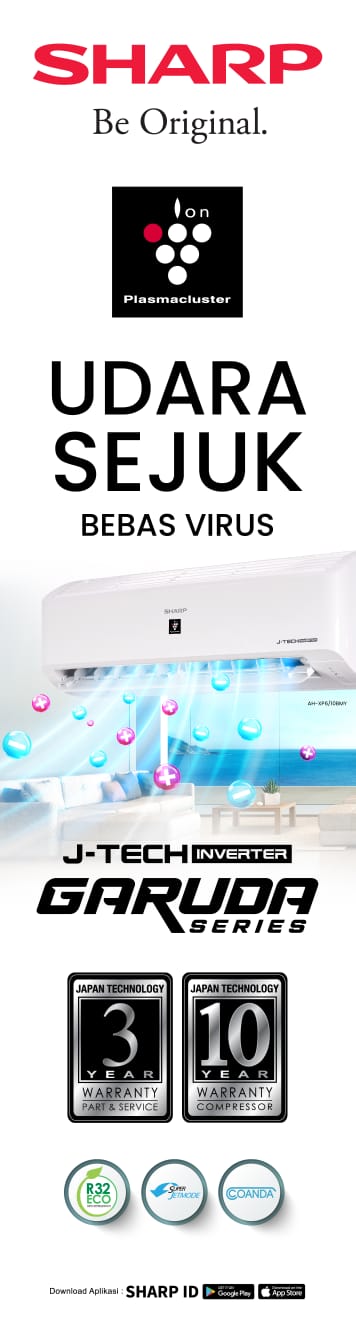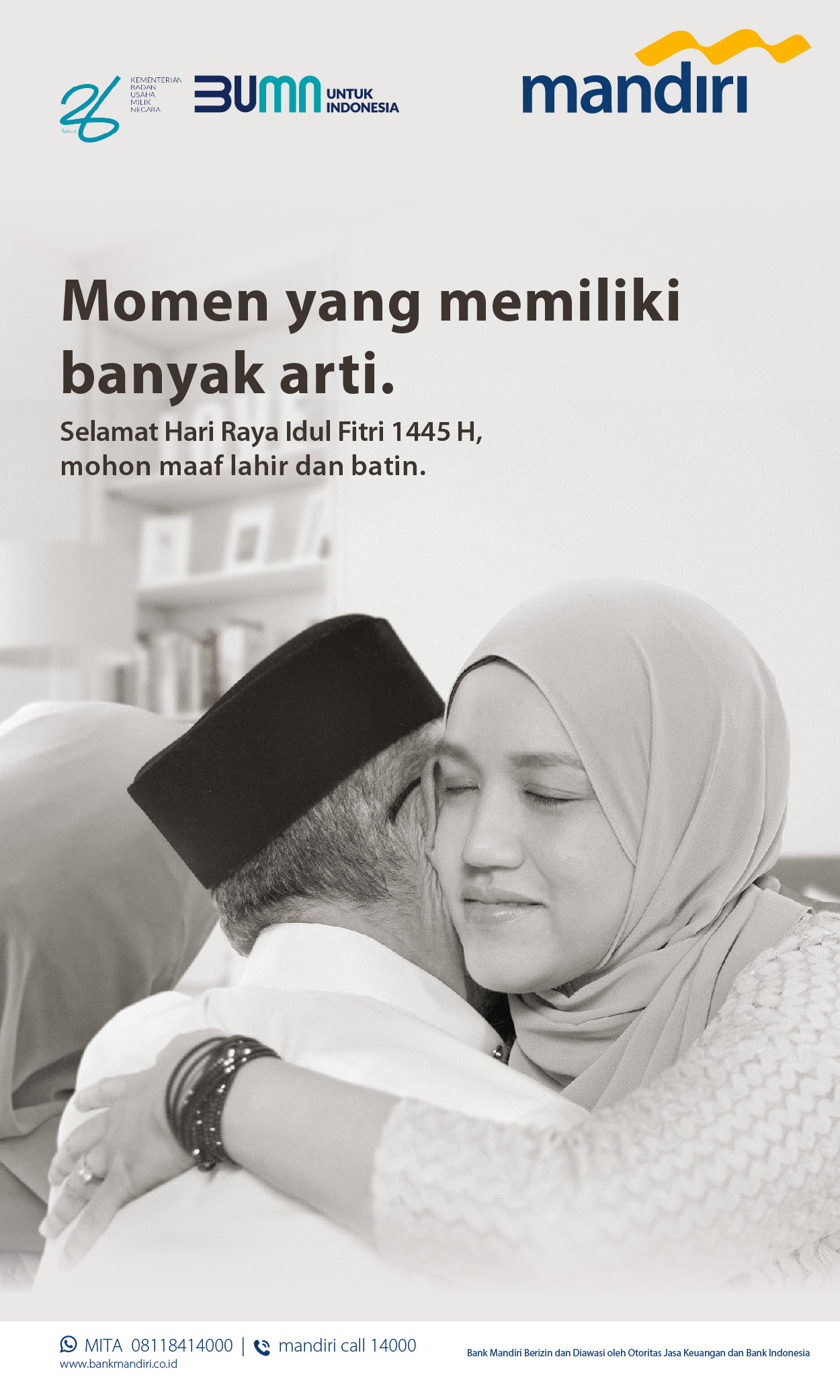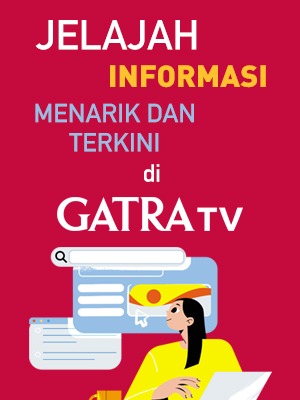Gatrareview.com - Pandemi Covid-19 mendorong para peneliti dan periset anak negeri membentuk korsorsium untuk mengembangkan inovasi alat kesehatan, skrining, obat-obatan hingga pembuatan vaksin untuk penanganan Covid-19. Konsorsium ini diinisiasi Kementerian Riset Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenrisetk/BRIN). Selang dua bulan dibentuk, konsorsium ini sudah berhasil merilis sejumlah produk hasil inovasi, mulai dari rapid tes kit, ventilator, laboratorium berjalan untuk uji tes Covid-19 hingga aplikasi pendeteksian sebaran Covid-19 berbasis AI (artificial intelligence). Kini, produk hasil inovasinya sudah diproduksi massal.
Untuk mengetahui apa saja inovasi dan capaian dari konsorsium ini, tim Gatra review secara khusus mewawancarai Menteri Ristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro. Wawancara dilakukan pada Selasa, 4 Agustus lalu melalui webinar. Berikut kutipannya.
Apa peran Kemenristek/BRIN dalam pengembangan inovasi untuk membantu menangani pandemi Covid-19?
Kami di kementerian dalam penanganan Covid-19 ini membentuk konsorsium riset dan inovasi Covid-19. Tentunya di dalam rapat pertama itu, kita langsung diskusi apa-apa saja yang ingin kita kerjakan dan kita fokuskan, apa yang menjadi quick win (program percepatan). Quick win di sini tentunya, selain yang dihasilkan nanti bermanfaat dan bisa berdampak langsung, juga bisa diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat. Karena kalau kita bicara penyakit, tentunya kita tidak bisa menunda terlalu lama.
Setelah berjalan sekitar dua bulan, kita pada 20 Mei lalu melakukan peluncuran dari produk hasil konsorsium tersebut. Kebetulan memanfaatkan waktu 20 Mei, Harkitnas (Hari Kebangkitan Nasional), kita labelkan momen itu sebagai kebangkitan inovasi Indonesia. Tentunya bicara quick win tadi, beberapa program yang menjadi prioritas kemudahan bisa mulai di produksi dan di perbanyak sesudah 20 Mei itu. Yang pertama adalah yang terkait dengan masalah pengujian. Kenapa pengujian ini penting, karena kita tahu semua ini (Covid-19) adalah penyakit yang menularnya begitu cepat dan begitu mudah. Sehingga perlu sekali yang namanya skrining maupun diagnosis.
Untuk mengantisipasi skrining dan diagnosis yang begitu besar, maka salah satu yang menjadi prioritas dan bisa diselesaikan itu adalah rapid test. Mereknya saat ini namanya RI-GHA, di mana rapid test ini yang pertama benar-benar dibuat, didesain, dan dikembangkan oleh anak bangsa. Jadi kita bisa klaim ini sebagai inovasi Indonesia. Karena kita ingin sekali berbagai target alkes (alat kesehatan) ini bisa di kembangkan dan diproduksi di Indonesia.
Bagaimana progres terbaru dari upaya pengembangan inovasi tersebut?
Untuk perkembangan rapid test sendiri, awalnya hanya ada satu perusahaan yang memproduksi. Skala kecil, hanya 100.000 unit per bulan. Namun sekarang, mulai September nanti sudah bisa produksi skala sampai dengan 1 juta unit per bulan. Dan kemungkinan setelah itu lebih besar lagi.
Selain rapid test, yang terkait dengan skrining dan didiagnosis, ada pula PCR (polymerase chain reaction) test kit. PCR tes kit ini adalah test kit yang dipakai dalam mesin RT-PCR (realtime PCR). Jadi mesinnya sendiri memang masih impor, tapi untuk bisa melakukan pengujian terhadap virus Covid-19 itu, maka perlu test kit yang sekarang sudah bisa diproduksi. Dan sekarang sudah bisa diperbanyak oleh PT Biofarma.
Selain itu, ada pengembangan Lab (laboratorium PCR test) BSL2 yang mobile, artinya lab bisa di pindah-pindahkan. Dan itu kita buat di semacam kontainer, dan di dalamnya minimal ada ekstraksi RNA dan mesin RT-PCR. Dan sudah memenuhi prasyarat Lab BSL2 yang dibutuhkan untuk pengujian Covid-19. Saat ini tentunya lab yang mobile tersebut sudah mulai beredar di berbagai daerah, terutama untuk menutupi kebutuhan daerah yang mana jumlah Lab BSL2 yang permanen masih sangat terbatas.
Bagaimana dengan pengembangan inovasi di bidang obat-obatan dan penyembuhan Covid-19?
Untuk pengobatan dan penyembuhan ini kita bagi atas beberapa kategori. Pertama, kita sekarang mengembangkan suplemen herbal khusus Covid-19. Tentunya sudah kita ketahui banyak sekali klaim terkait suplemen herbal atau obat herbal ini. Nah, di sini kita ingin melakukannya dengan benar. Dalam pengertian bahwa suplemen herbal khusus Covid-19, kalau ingin klaim bahwa ini memang untuk Covid-19, harus melalui proses yang namanya uji klinis.
Saat ini kita sudah mulai untuk beberapa produk suplemen yang sudah disetujui BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Itu adalah syarat pertama. Jadi artinya aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kemudian untuk memastikan bahwa ini efektif untuk Covid-19, harus uji klinis. Saat ini kami sudah menjalin kerjasama dengan RS Darurat Wisma Atlit (Jakarta), serta persatuan dokter, untuk memastikan nanti proses uji klinisinya sesuai protokol dan standar yang di tetapkan.
Kedua, kita juga berpartisipasi aktif untuk plasma konvalesen. Ini adalah plasma darah yang diambil dari pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Yang kemudian dicek kadar antibodinya, kalau cukup tinggi, maka plasma tersebut bisa diberikan kepada pasien yang sedang sakit akibat Covid-19. Ternyata dari proses yang berjalan selama ini, tingkat penyembuhannya cukup tinggi. Sangat membantu untuk pasien utamanya dalam kondisi agak berat.
Nah, terkait dengan itu, kami juga kembangkan stem cell. Terutama untuk mengganti jaringan paru-paru yang rusak, karena Covid-19 ini kan serangannya ke paru-paru. Sudah ada beberapa kasus dimana stem cell ini bisa menyembuhkan pasien yang tadinya sudah sangat berat kondisinya. Kalau tadinya gambar toraks paru-parutnya putih semua yang artinya tidak berfungsi, setelah diobati dengan stem cell maka kondisi paru-parunya kembali seperti orang normal pada umumnya.
Terakhir untuk alkes dan pendukungnya. Yang paling menonjol adalah ventilator. Karena di awal pandemi kita tahu banyak rumah sakit yang kekurangan ventilator. Akhirnya dalam waktu singkat berhasil dikembangkan berbagai ventilator, yang paling tidak ada lima ventilator yang pengembangan dalam negerinya sudah dapat izin edar dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Kelimanya sudah diproduksi dalam jumlah besar dan sudah mulai dibagikan dan didistribusikan pada faskes (fasilitas kesehatan) yang membutuhkan. Dan yang dihasilkan juga bervariasi, ada yang untuk keperluan ruang rawat biasa dan ada juga untuk ruang emergency dan ruang ICU. Memang yang ICU masih membutuhkan pengembangan lagi karena sifatnya invasif. Tapi yang lainnya praktis sudah bisa di buat dan sudah dia pakai di berbagai RS.
Selain ventilator tentu ada APD (alat pelindung diri) lain, tidak sekadar hazmat atau face shield, tapi juga ada yang namanya power air purifier respirator. Jadi ini untuk memastikan orang yang memakai hazmat bisa mendapatkan suplai oksigen yang bersih dan bebas virus. Dan kita juga terlibat dalam upaya pamungkas untuk Covid-19 yaitu vaksin. Yaitu vaksin merah putih yang pengembangannya dipimpin oleh LBM Eijkman. Dengan menggunakan platform protein rekombinan. Saat ini mereka melakukan kloning terhadap protein, baik itu spike atau protein N nya. Sehingga diharapkan bisa siap diujicobakan ke hewan, sebelum bisa segera masuk tahapan uji klinis terhadap manusia.
Konsorsium riset dan inovasi Covid-19 ini melibatkan banyak pihak, dari lintas kementerian, perguruan tinggi hingga pihak swasta. Bagaimana prinsip kerjanya?
Prinsip kerja kami dalam konsorsium adalah triple helic. Intinya sinergi di antara tiga pihak yang sangat berperan dalam menentukan dan mempengaruhi terjadinya inovasi. Siapa saja? Pertama tentunya dari sisi penelitinya atau akademisi. Tentunya yang ada di sini adalah dari perguruan tinggi, demikian juga dari lembaga penelitian seperti yang berada di bawah koordinasi kami yaitu BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), LIPI (Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia), dan lain-lain. Kemudian juga tentunya dari penelitian yang dilakukan individu seperti yang dilakukan diaspora kita di luar negeri maupun peneliti di bawah lingkup swasta atau BUMN. Itu adalah satu pilar helix-nya.
Kedua dalah pihak industri atau dunia usaha. Tentunya yang ada adalah berbagai BUMN, tidak hanya BUMN farmakes (farmasi dan kesehatan), tapi juga melingkupi BUMN industri pertahanan. Selain itu juga ada swasta, baik dari perusahaan farmasi maupun manufaktur yang juga terlibat. Kita juga melibatkan di sisi swasta ini tentunya asosiasi dokter, sebagai pihak yang menjadi pengguna alat ini dan rumah sakit (RS). Karena RS lah yang nanti akan menggunakan produk-produk inovasi itu nantinya.
Untuk dua pilar tersebut, harus ada pihak yang memfasilitasi agar kedua pilar tersebut bisa sinergi, dan pilar itu adalah pemerintah. Bukan hanya kami sebagai otoritas di bidang riset dan inovasi, tapi tentunya juga melibatkan Kemenkes. Karena mereka yang menentukan ijin edar dan sebagainya. Juga BPOM yang punya wewenang di bidang obat. Demikian juga Kementerian BUMN, Kemenperin (Kementerian Perindustrian), yang juga banyak terlibat soal hilirisasi hasil riset, ditambah dengan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang mana banyak peneliti itu berasal dari perguruan tinggi.
Pengimplementasian triple helix ini apa bisa berjalan mulus?
Jadi memang Covid-19 ini memberikan kesempatan pada kami, untuk bisa mengimplementasikan triple helix dalam kondisi sebenarnya dalam kondisi yang memang darurat dan waktunya pendek. Tapi karena environment-nya sudah terbangun, maka triple helix ini bisa berjalan mulus. Apalagi demand dari sisi pengguna baik pemerintah, RS, dan Masyarakat ini udah cukup jelas. Jadi peneliti tinggal merespons apa yang menjadi kebutuhan dan kemudian industri meresponnya dengan memproduksi inovasi atau temuan tersebut dalam jumlah yang massal.
Apakah bahan baku produk-produk inovasi ini kandungan TKDN (tingkat komponen dalam negeri)-nya sudah tinggi?
Kunci perbedaan inovasi dengan yang sekadar produksi adalah hasil inovasi. Kalau yang hanya assembly itu yang cuma disebut produksi Indonesia, karena lokasinya itu dibuat di Indonesia. Nah, produk yang saya bicarakan dari awal itu adalah hasil inovasi. Kalau hasil inovasi, maka dari tahap desain, pengembangan, dan penelitian dilakukan oleh pihak Indonesia. Dan kita upayakan optimalisasi TKDN dalam bahannya.
Jadi, kalau dalam TKDN jelas bahan lokalnya mendominasi. Meskipun, memang, ada beberapa instrumen yang masih membutuhkan impor. Contohnya untuk rapid test, itu masih butuh reagen yang tetap harus impor. Walaupun saat ini kita sedang mengupayakan reagen yang dikembangkan oleh kita sendiri dan itu membutuhkan waktu. Tapi yang paling penting dalam dua bulan itu, kita bisa bikin rapid test yang desainnya dari Indonesia, tapi memang masih pakai reagen impor. Tapi kalau dihitung TKDN nya jelas itu komponen lokal mendominasi.
Untuk ventilator, ada yang 100% Indonesia dari bahan dan materialnya, tapi ada juga yang sebagian masih impor. Tapi poinnya kalau TKDN itu kita selalu mengarahkan kepada TKDN yang sesuai harapan kita diatas 60%-70%. Demikian juga untuk alat-alat lain. Bahkan untuk obat, arah kita hanya obat herbal. Kita ingin mengembangkan obat atau suplemen herbal yang otomatis bahannya itu datang dari kita sendiri. Ekstraksinya kita yang lakukan. Jadi tidak tergantung bahan baku obat yang berasal dari kimia yang otomatis harus impor.
Berkaitan dengan vaksin Covid-19, apa perbedaan vaksin yang dikembangkan di Cina, Sinovac, dan vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Eijkman dan Kemenristek/BRIN?
Perbedaan pertama pada platform. Kalau Cina, Sinovac itu menggunakan platform inactivated virus atau virus yang dilemahkan. Kalau virus Merah Putih yang dikembangkan Eijkman sejak Maret, itu platformnya protein Rekombinan. Memang kalau yang Sinovac itu saat ini sudah sampai tahap uji yang lebih cepat, karena juga di dukung oleh dana penelitian yang sangat besar, maka dia sudah masuk uji klinis tahap tiga. Sedangkan kalau vaksin Merah Putih ini tentunya kita ikuti tingkat kecepatannya, kita harapkan tahun ini sudah selesai uji di hewan. Dan tahun depan (2021) sudah di uji di uji klinis, sebelum akhirnya diproduksi masal untuk vaksinasi.
Jadi, kita berjalan double track. Karena kalau vaksin ini kan kita ingin dapat akses secepat mungkin, untuk vaksin yang efektif. Jangan lupa, kalau vaksin itu biar dia di uji klinis, belum ada jaminan bahwa vaksinnya efektif. Karena kita perlu analisa hasil uji klinis tersebut. Kenapa dilakukan uji klinis, ya biar vaksinnya efektif.
Vaksin Eijkman ini perbedaan lainnya menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia,sedangkan vaksin sinovac, otomatis menakai isolat virus yang berkembang di Cina. Tapi kita ridak berhenti di platform rekombinan itu, kita juga sedang menjajaki dari tim vaksin Merah Putih pada platform lain, baik dari platform inactivated virus maupun metode terbaru mRMA.
Untuk pembiayaan riset dan inovasi yang dilakukan konsorsium ini, dari mana anggarannya?
Memang ketika pandemi ini terjadi dilakukan realokasi anggaran. Dimana banyak atau hampir semua K/L (kementerian/lembaga) itu di potong budgetnya dan dialihkan pada penanganan kesehatan. Kami juga begitu, angggaran kami dipotong 30%, dari Rp2,7 trilyun menjadi Rp1,8 trilyun. Kemudian untuk bisa eksekusi kegiatan riset inovasi Covid-19 ini, kebetulan kami memanfaatkan hasil kelolaan dana abadi yang ada di LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Di sana ada dana abadi pendidikan dan dana abadi penelitian. Dari kelolaan dana itu, kami berhasil mendapatkan Rp90 milyar yang kemudian dipakai untuk kegiatan risbang (riset pengembangan), berbagai alkes dan obat maupun tes kit yang tadi saya sebutkan.
Di luar itu, kita juga apresiasi baik perguruan tinggi, lembaga penelitian, yang juga menyisihkan sebagai anggarannya untuk kegiatan Covid-19 ini. Akhirnya kami mengombinasikan angggaran yang kami berikan para peneliti dan pengembang tadi, dikombinasi dengan dana mereka sendiri, dan bahkan ada juga yang melakukan crowdfunding. Jadi, mengumpulkan dana dari masyarakat, seperti ventilator ITB (Institut Teknologi Bandung) yang mengembangkan crowdfunding.
Tentunya tahapan kami sebagai Kemnristek/BRIN, adalah bagaimana kami melakukan riset sampai ditemukan prototipe, yang siap untuk diuji. Kalau anggaran untuk melakukan industrialisasi atau produksi dalam jumlah massal, itu sudah di luar ranah kami. Itu jadi anggaran swasta, BUMN, yang memproduksi. Dan yang terpenting, anggaran di Kemenkes untuk melakukan pengadaan. Seperti rapid tes, PCR tes, pengadaan terapi obat, alkes, dan lain-lain. Intinya kita bisa optimalkan dana yang ada untuk bisa mendorong riset dan invoasi terkait Covid-19.
Setelah meluncurkan produk hasil inovasi pada 20 Mei lalu, kabarnya pada 10 Agustus ini akan diluncurkan lagi produk terbaru. Benarkah?
Betul. Dari 20 Mei tentunya kita tidak berhenti melakukan inovasi, dan pertama itu yang penting hilirisasi dari produk tersebut. Misal di rapid test, tadinya kita sulit mencari pabriknya. Alhamdulilah sekarang sudah dapat beberapa mitra yang bahkan bisa memproduksi totalnya 1 juta unit per bulan. Ini tentunya melegakan. Perkembangan yang akan kami sampaikan pada 10 Agustus nanti, salah satunya pengembangan alat rapid test, baik dalam bentuk rapid test yang lebih akurat maupun rapid test yang lebih mudah dipakai. Jadi ini pengembanganan produk yang akan kami sampaikan juga.
Perkembangan lainnya adalah sudah ada dua kandidat alternatif dari mesin RTPCR. Jadi kita tidak berupaya membuat mesin RTPCR sendiri yang memang mahal harganya kalau diimpor, tapi kita membuat alternatifnya. Tes pengujian berbasis diagnosa atau berbasis swab, tapi menggunakan pendekatan lain. Ada dua pendekatan yang akan kami kenalkan nanti. Pertama adalah RTLAM, itu adalah pengujian melalui swab atau saliva kita, dan kemudian bisa memberikan hasil dalam waktu satu jam. Jadi bukan rapid test, tapi PCR test dengan waktu yang lebih cepat, hanya satu jam. Dengan menggunakan kekeruhan.
Jadi kalau RTPCR itukan menggunakan kategori negatif-positif sesuai apa yang ditemukan oleh mesin. Tapi kalau RTLAM ini kemudian saliva yang ditemukan dicek dalam tabung itu kelihatan. Kalau keruh artinya positif, kalau bening artinya negatif. Yang pasti, ini lebih murah, karena kalau dihitung per pengujian ini hanya Rp100.000 per pengujian.
Kedua, ada yang namanya mesin SPR (suspected plasmonic resonance). Yang dia pakai keperluan patogen atau keperluan mengecek virus. Ini juga bisa dipakai untuk Covid-19. Kebetulan di BPPT dan ITB, mereka mengembangkan microchip sensor yang membuat mesin SPR ini berfungsi layaknya RTPCR. Kelebihannya tentu mesinnya jauh lebih murah. Kedua dengan microchip sensornya, maka kita tidak perlu impor reagennya. Karena reagennya bisa dibuat sendiri. Jadi ini beberapa produk yang akan kami sampaikan sebagai laporan ke Presiden.
Selain itu tentu juga ada ventilator yang kita harapkan bisa jadi ventilator di ICU. Karena ini adalah tipe yang paling canggih, dan bisa dipakai pasien yang harus berada di ICU. Itu beberapa produk yang akan kami sampaikan. Selain itu juga ada penanganan Covid-19 ini dengan berbasis AI (artificial intelligence). Kita menggunakan pendekatan digital untuk pengadaan Covid-19 dengan AI, dan diperkuat data yang lengkap. Kita harap nanti kita bisa punya semacam health kit task force maupun pendekatan untuk bisa mendeteksi Covid-19 sedini mungkin.
Dengan adanya pandemic Covid-19 ini, bagaimana peta industri kesehatan di Indonesia ke depan?
Kita akan memulai sesuatu kondisi ketika awal pandemi, dan juga sejatinya sudah terjadi jauh sebelumnya, bahwa masalah kesehatan di Indonesia ini rupanya belum di dukung oleh kemandirian kita sendiri. Sebagai contoh, dari data, 90% alkes impor, juga bahan baku obat utamanya yang kimia itu 95% impor. Artinya, menangani kesehatan 250 juta penduduk kita sendiri kita sama sekali belum membangun ekosistem kemandirian yang memadai, baik alkes maupun bahan baku obat.
Makanya momentum Covid-19 ini juga dapat dimanfaatkan untuk mulai bangun ekosistemnya. Paling tidak untuk Covid-19 ini ekosistemnya sudah terbangun. Karena kita sudah tahu siapa yang bisa melakukan, risbangnya, baik alkes mampun obat. Dan kita juga tahu siapa industri yang bisa produksi dalam jumlah besar, dan juga kita tahu mekanisme pengadaannya. Karena pemerintah harus di depan ketika bicara pengadaan inovasi anak bangsa.
Kalau untuk inovasi anak bangsa, ditahap awal pemerintah yang harus berikan dukungan dalam bentuk pengadaan. Kalau dia mencapai skala produksi atau ekonomi tertentu, barulah dia bisa dilepas untuk mendapatkan market secara komersial, baik dalam dan luar negeri. Harapan kedepannya kita bisa mengurangi kebutuhan impor alkes. Kalau sekarang kita baru bisa memproduksi test kit, ventilator, dan-lain-lain, saya percaya ke depan kita bisa membuat sampai ke alat rontgen, atau alat kesehatan lain yang sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat. Kita fokus pada alkes yang dipakai masyarakat kita dalam rangka menjaga kesehatan mereka.
Kalau obat, itu jelas, kita harus beralih ke bahan obat yang herbal. Jadi, tidak lagi bergantung pada bahan kimia. Otomatis, kita makin aktif lakukan penelitian untuk bahan baku obat yang nantinya bisa untuk penyakit non-communicable disease, yang memang banyak di Indonesia. Seperti serangan jantung, hipertensi, diabetes, kita harus kembangkan obat untuk penyakit-penyakit ini tapi basisnya herbal bukan kimia. Itu yang kita sebut obat modern asli Indonesia atau fitofarmaka.
Bagaimana keberpihakan Pemerintah pada produk inovasi anak bangsa ini?
Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita lakukan inovasi, di tahap awal otomatis pemerintah harus berada di depan, sebagai pihak yang menjamin adanya pengadaan terhadap hasil inovasi tersebut. Khusus untuk Covid-19, arahan presiden yang ditegaskan bahwa kalau kita sudah bisa membuat alkes maupun obat sendiri, maka kita harus kurangi impor atau bahkan setop impor alat dan obat yang sudah kita produksi sendiri tersebut. Itu arahan tegas.
Kedua, dari Kemenkes juga sudah committed untuk test kit, dia akan utamakan yang bisa kita produksi. Tentunya proposional, kita produksi berapa, mereka butuh berapa. Kalau masih harus ada yang di impor ya silakan, tapi yang pasti yang dalam negeri harus diutamakan. Demikian juga untuk ventilator. Untuk alat kesehatan maupun obat saya yakin ini akan menjadi jalan panjang, dan tidak mudah utnuk memenangkan kepercayaan konsumen dalam negeri.
Kalau mau jujur, penentu penggunaan alkes dan obat kan bukan di Direktur RS bukan di Kemenkes, tapi di dokternya. Hanya dokter yang bisa bilang saya mau pakai obat A, atau ventilator jenis X misalkan. Makanya pendekatan kita melibatkan asosiasi dokter dalam konsorsium, supaya mereka sadar bahwa putra-putri bangsa kita sendiri bisa membuat alkes dan obat. Dan harapan kami juga mereka memberikan masukan, alkes atau obat seperti apa yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Sehingga apa yang diproduksi nanti sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita pun harus adaptif terhadap kebutuhan itu.
Kita juga dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sudah membuat khusus katalog inovasi Indonesia. Jadi nanti ada bagian dari E-Katalog yang isinya produk yang kita definisikan sebagai inovasi indonesia, temasuk alkes dan obat.
Selama ini, produk hasil inovasi anak bangsa seringkali mentok di proses hilirnya. Apakah perlu ada suatu kebijakan terpadu atau dibentuk badan khusus? Solusinya seperti apa?
Solusinya sejatinya ada pada badan baru yang melekat pada kami, yaitu BRIN. Memang kalau kita bicara hanya ristek, maka kita memang lebih berat ke satu sisi yaitu pada sisi litbang, kurang banyak bicara soal hilirisasi. Karena kalau bicara riset, itu adalah aktivitas yang sifatnya sangat hulu. Termasuk riset pasar atau terapan.
Kemudian teknologi, itu adalah pendekatan yang dipakai. Dan teknologi yang dipakai belum tentu bisa dihilirisasi. Karena itulah, dibentuk BRIN. Di mana ada kata baru yang menjadi portofolio kabinet, yaitu inovasi. Dengan inovasi maka hilirisasi menjadi suatu keharusan. Istilahnya, KPI (key performance indicator) kami nanti tergantung seberapa banyak kita bisa hilirisasi hasil riset tersebut. Kenapa di masa lalu atau mungkin sampai sekarang masih banyak terjadi, misalkan temuan penelitian yang tidak terjadi sesuatu yang sifatnya komersial atau market. Jawabannya simpel, karena ada GAP yang sangat besar dari sisi penelitian dan sisi dunia usaha.
Itu terjadi karena komunikasi yang tidak terbangun atau tidak ada pihak yang melakukan fasilitasi atau komunikasi antar-dua pihak tersebut. Jadi itu yang mendorong kami melakukan sisi penelitian dan industri agar saling ketemu. Dan resep kami, itu adalah yang industri harus mau lihat lebih ke hulu, yang peneliti harus mau lihat lebih ke hilir. Intinya, masing-masing tidak bisa bertahan di posisi masing-masing. Harus saling komunikasi dan saling paham. Yang peneliti harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang industri jangan hanya berpikir bahwa dia tidak tahu apa yang dilakukan peneliti, pokoknya kalau (produknya) tidak ada di Indonesia maka dia langsung beli di luar.
Kalau dia mau lihat lebih ke hulu, maka industri juga akan lihat peneliti Indonesia itu bisanya apa, kemudian diidentifikasi kebutuhan tertentu, industri bisa menyampaikan ke peneliti. Misal dia butuh alkes, butuh alat transportasi seperti ini, maka keduanya bisa matching dan GAP itu bisa terkikis. Memang salah satu kunci keduanya bisa terjadi, itu harus ada insentif pajaknya. Ini saya masih nunggu peraturan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk implementasi dari super tax deduction, yang peraturan pemerintahnya sudah keluar tahun lalu. Tapi kami masih menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya agar bisa teroperasional di lapangan. Kalau ada super tax deduction ini, otomatis pengusaha akan tertarik untuk masuk research and development.
Pandemi Covid-19 ini mampu mendorong para peneliti dan periset untuk saling bekerja sama mengembangkan inovasi. Bagaimana menjaga gairah riset para peneliti dengan menggunakan momentum ini untuk ke depannya?
Kebetulan di Kemenristek/BRIN ada dua program utama yang bisa menjaga momentum tersebut dan didukung oleh anggaran yang cukup memadai. Pertama mekanisme penelitian di perguruan tinggi. Ini adalah bagian dari dana pendidikan yang didedikasikan untuk penelitian di perguruan tinggi. Ini sudah kita lakukan dengan mekanisme hibah bersaing. Jadi masing-masing perguruan tinggi penelitinya mengajukan proposal dan kita nilai dengan tidak hanya melihat kompetensi peneliti tapi relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
Kedua kita juga punya Prioritas Riset Nasional dalam kurun waktu lima tahun dengan target menghasilkan sekitar 49 produk dengan 12 produk prioritas dan tiga produk superprioritas. Tentunya kita harapkan peneliti yang terlibat ini bisa optimal karena didukung anggaran yang memadai.



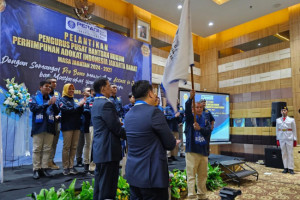

_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)