Mahkamah Agung mengetuk aturan baru soal hukuman koruptor secara kategoris. Tujuannya untuk menekan disparitas putusan hakim. Melampaui porsi UU Tipikor?
Dua puluh satu pasal tertera di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 Tahun 2020, lengkap dengan matriks rentang putusan. Beleid yang ditandatangani Ketua MA, Muhammad Syafrudin, ini pada intinya memberikan pedoman bagi seluruh hakim tindak pidana korupsi (tipikor) dalam menjatuhkan putusan.
Yang diatur MA dalam PerMA ini adalah urusan lama dalam peradilan Indonesia. Yaitu soal disparitas hukuman koruptor. Sejak 2016 saja, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sudah mulai bersuara soal perbedaan putusan hakim dengan tuntutan jaksa yang terlalu lebar (menciptakan disparitas).
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MaPPI) menemukan, sepanjang 2011-2015 ada 166 putusan yang masuk dalam kategori disparitas hukuman. Angka ini ditemukan dalam 587 putusan pengadilan tipikor dan korespondensi hukum dengan 689 terpidana korupsi. Hal ini kemudian memantik ide tentang evaluasi penjatuhan hukuman, utamanya bagi terpidana korupsi.
Gayung bersambut, MA pun memahami pentingnya membuat pedoman bersama dalam menjatuhkan hukuman bagi para koruptor. Juru bicara MA sekaligus Hakim Agung, Andi Samsan Nganro, menyebut langkah awal pembentukan PerMA ini sudah berlangsung sejak 2018. Diawali kerja sama MA dan MaPPI dalam membentuk kelompok kerja (pokja) penyusunan PerMA ini.
Menurut Andi, kedudukan PerMA ini menjadi penting ketika sistem kamar sudah diberlakukan di MA sejak 2011. Sistem kamar ini, seperti yang juga dilakukan di MA Belanda atau Hoge Raad, membagi Hakim Agung di MA menjadi lima kelompok: pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. "Atas dasar itu kita bentuk pokja," ujarnya kepada Wahyu Wachid Anshory dari Gatra.
PerMA ini, Andi melanjutkan, sengaja dibuat hanya untuk pedoman para hakim dalam menangani dan menjatuhkan pidana dalam perkara tipikor yang menyangkut kerugian keuangan negara bagi para hakim tipikor tanpa kehilangan independensinya.
Pedoman yang disebut Andi sebenarnya mengatur berat-ringannya hukuman yang didasarkan pada tiga pertimbangan, yakni kerugian negara, kesalahan terdakwa, dan terakhir dampak serta keuntungannya bagi terdakwa (lihat infografis).
Dengan PerMA ini diharapkan, ke depan hakim tipikor yang mengadili perkara korupsi --terlebih jika terbukti melanggar Pasal 2 atau 3 UU Tipikor--lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi keadilan, keserasian, dan kemanfaatan. Terutama jika dikaitkan dengan satu perkara dengan perkara lainnya yang serupa. "Dengan terbitnya pedoman pemidanaan ini pula, diharapkan hakim tipikor dapat menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa," kata Andi.
Selain data disparitas dari MaPPI, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga tak mau kalah dengan mengeluarkan temuannya tentang tren hukuman ringan bagi terpidana korupsi. Sejak 2013-2019, ICW memantau putusan hakim tipikor masih terlalu rendah, hanya berkisar di angka dua tahun lima bulan.
Di tengah kenyataan itu, ICW mengapresiasi keluarnya PerMA yang mengatur soal tentang hukuman terpidana korupsi. "PerMA diharapkan dapat menjadi jawaban atas problematika peradilan tipikor yang kerap terdapat kali disparitas hukuman yang pada akhirnya juga berujung pada vonis ringan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Muhammad Almer Sidqi dari Gatra, Senin lalu.
Namun, Kurnia menambahkan, PerMA Nomot 1/2020 itu semestinya juga mengatur soal sanksi terhadap para hakim yang tidak mengikuti aturan itersebut.
Adanya disparitas hukuman bagi terpidana korupsi juga diamini Wakil Ketua MPR, Arsul Sani. Menurutnya, dalam proses peradilan, meski semua alat bukti dan fakta sudah sebanding dengan pasal yang diajukan, tetap saja ada disparitas hukuman yang cukup lebar.
Meski dilandasi niat baik, PerMA ini, pada hemat Asrul, masih perlu dikaji dari sisi politik hukum pembuatan aturan. Beleid ini dinilai sudah mengambil porsi UU Tipikor yang tingkatnya lebih tinggi ketimbang peraturan lembaga tinggi negara. "Muatan yang ada sebagiannya masuk dalam hukum pidana materiil yang semestinya menjadi materi muatan undang-undang, misalnya di RKUHP atau Revisi UU Tipikor," ujar Arsul kepada Muhammad Guruh Nuary dari Gatra.
Menurut Arsul, hakim sebenarnya tidak butuh pedoman dalam menjatuhkan putusan. Karena, hakim tentu tak bisa diintervensi oleh pihak mana pun, tidak juga oleh MA. Terbitnya PerMA ini justru bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengurangan independensi dan kemandirian hakim. "Koreksi terhadap vonis hakim dilakukannya dalam bentuk vonis oleh hakim yang lebih tinggi, bukan dengan memberikan arahan tentang vonis dalam aturan di bawah UU," ia memaparkan.
Dalam pandangan Arsul, Belanda sebagai kiblat ilmu hukum Indonesia tidak membuat pedoman semacam PerMA ini, melainkan hanya membangun kesepahaman bersama di antara para hakim. Membangun kesepahaman ini bisa dengan banyak cara, seperti rapat internal yang kemudian mengembangkan sekadar petunjuk teknis, bukan aturan yang mengikat. "Sedangkan di Prancis dalam bentuk guidelines, itu pun di jajaran jaksa, bukan di kalangan hakim," ucapnya.
Arsul mafhum bahwa sandaran terbentuknya PerMA ini salah satunya adalah tidak adanya aturan dalam UU Tipikor yang secara khusus memberikan variabel penilaian bagi hakim tipikor. Tapi, jika dilihat lebih jeli, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebenarnya sudah mulai ada aturan yang mengarah pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara, termasuk tipikor. "Cuma kan ini belum disahkan. Nanti kalau sudah disahkan, maka hal-hal yang ada dalam Perma dengan sendirinya menjadi tidak berlaku," tuturnya.
Dengan keluarnya beleid MA ini, Asrul melanjutkan, di kalangan politisi Senayan, terbangun kesan MA sudah menjadi lembaga legislatif yang mengeluarkan aturan dengan materi UU. Hal ini juga sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh guru besar hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir. Pakar hukum yang juga sebagai salah seorang pemikir di balik RKUHP ini melihat adanya persoalan dalam pembentukan PerMA ini.
Mudzakir melihat, Pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor sebenarnya sudah memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. "Kalau diberi pedoman lagi, sama saja membelenggu hakim," ujarnya.
Belum lagi dengan soal proporsionalitas keadilan yang semestinya menjadi pijakan hakim dalam memutus suatu perkara. Banyak faktor yang melandasi seseorang melakukan korupsi. Pada titik ini, menurut Mudzakir, hakim semestinya diberikan ruangan seluas-luasnya untuk mempertimbangkan hukum yang berdasarkan keadilan.
Jika ruang pertimbangan hakim sudah sangat kecil, kata Mudzakir, maka hakim tidak lebih dari kalkulator yang menghitung besar kecilnya vonis didasarkan pada angka-angka dalam tabel semata. Lagi pula, persidangan hanya akan menjadi formalitas belaka dengan putusan yang sudah bisa diketahui sebelumnya.
Aditya Kirana



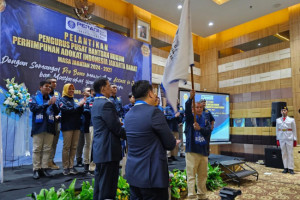

_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)















