
Jakarta, gatra.net - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berpendapat bahwa ambang batas atau Presidential Threshold (PT) akan melahirkan "duittokrasi" yang membunuh demokrasi.
"Duittokrasi itu berangkat dari kata duit. Artinya uang membunuh demokrasi kita. Jadi saya istilahkan duittokrasi," kata Denny, Senin (22/6).
Duittokrasi terjadi bukan hanya sekadar jual beli suara (vote buying) tetapi juga jual beli tiket untuk kandidat yang akan berlaga dari satu partai, dan berbagai praktik lainnya yang merupakan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, praktik duittokrasi ini bisa dirasakan ketika capres-cawapres sedang mencari dukungan dari partai politik akibat adanya ketentuan ambang batas atau PT. Untuk menjadi kandidat, tak jarang harus memberikan mahar kepada partai politik agar bisa diusung menjadi capres-cawapres.
"Pada dasarnya itu korupsi pemilu. Jadi ya selama kita masih permisif dengan praktik-praktik korupsi pemilu, maka pemilu kita hasilnya tidak maksimal," katanya.
Menurut Denny, ini akan menjadi rutinitas yang melahirkan potensi korupsi ketika pemimpin-pemimpin itu akhirnya terpilih dan menjabat. Agar tidak terjadi, maka sejak pemilu kepala daerah, pileg, dan pilpres, harus bersih dari praktik duittokrasi.
Selain itu, Denny yang juga menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat gelaran Voice for Change, lebih jauh menyampaikan, ambang batas atau PT akan mereduksi pilihan raykat.
Pasalnya, lanjut Denny, membatasi rakyat untuk mendapatkan pilihan. Sebab, hanya yang lolos PT saja yang bisa mengajukan capres-cawapres. Padahal, tidak ada ambang batas pun tidak menyebabkan semua orang bisa secara mudah melenggang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres.
"Pada tahun 2004 pas pertama kita kali pilplres, cuman 5 pasang. Kan enggak banyak-banyak juga. Itu kan tanpa batasan Presidential Threshold karena baru pertama. Setelah itu baru muncul," ungkapnya.
Kedua, lanjut Denny, presidential threshold cenderung menghadirkan pasangan yang lebih sedikit, bahkan hanya 2 pasang sehingga masyarakat menjadi terbelah atau 2 kubu yang saling berhadap-hadapan.
"Yang penting dari semua ini, esensi dari pemilihan langsung itu tidak tereduksi melalui PT. Itu yang paling penting, jangan karena alasan nanti takut panjang dan segela macam, terus esensi pilihan rakyat dikebiri," ujarnya.
Terakhir, Denny menegaskan, kalau konsisten pada konstitusi, maka seharusnya tidak perlu ada ketentuan ambang batas. "Kalau kita konsisten dengan UUD, itu kan disebutnya partai dan partai politik mecalonkan calon presiden. Tidak disebutkan ambang batasnya. Jadi kalau pendekatannya adalah pendekatan konstitusi, meskinya tidak ada syarat ambang batas," katanya.
Menurutnya, ambang batas tersebut bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945. "Ya kalau sisi kedaulatan negara bukan berapa persennya yang menjadi masalah, apakah 20% tidak boleh, 10% boleh atau 5% sesusai parliamentary threshold, bukan persentasi yang mejadi isu," ujarnya.
"Dari sisi kacamata konstitusi, yang menjadi masalah adalah berapa pun syaratnya, 0% selama ada syarat PT, itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi memang PT dari kaca mata konstitusi itu bermasalah. Sebaiknya tidak ada," ujarnya.
Sementara itu, peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. R Siti Zuhro, menilai bahwa syarat presidential treshold dalam pemilihan presiden 2019 telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena hanya menghasilkan 2 capres-cawpres.
Menurut Siti, esensi pemilu ini adalah menghadirkan kompetisi yang sehat dan beradab serta mempromosikan integritas dan kualitas pasangan calon, bukan malah menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi, karena calonnya tunggal.
Atas dasar itu, lanjut Siti, semangat yang harus dibawa dalam Revisi UU Pemilu ini adalah untuk mendorong munculnya lebih dari 2 pasangan calon. "Jadi calon itu harus lebih dari 2 pasangan sebagai ikhtiar transisi dan pembelajaran demokrasi, baik untuk elite maupun masyarakat," ujarnya.
Seperti diketahui, usulan kenaikan ambang batas pencalonan presiden memunculkan berbagai pandangan partai politik (parpol) dan mewarnai revisi UU Pemilu yang akan segera dibahas di parlemen, yakni Komisi II DPR. Revisi UU ini sudah masuk dalam prolegnas.



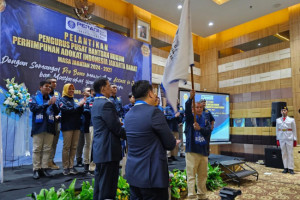

_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)















