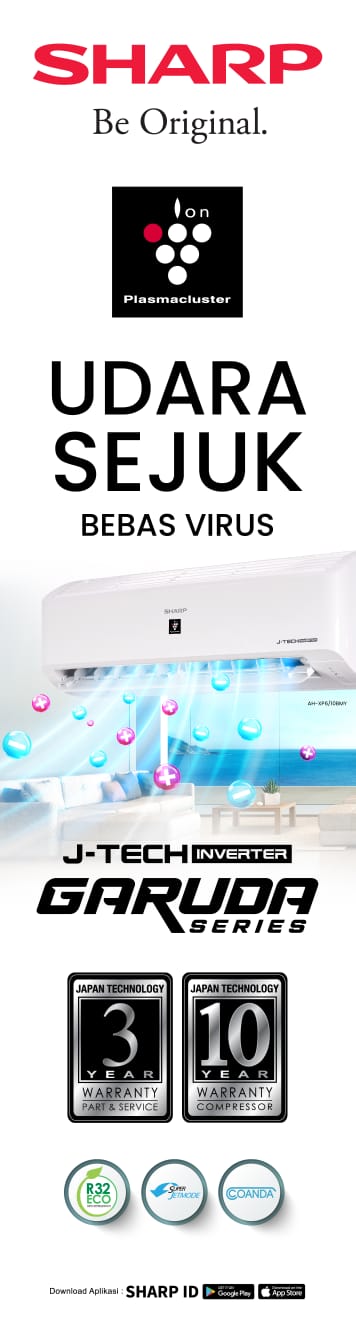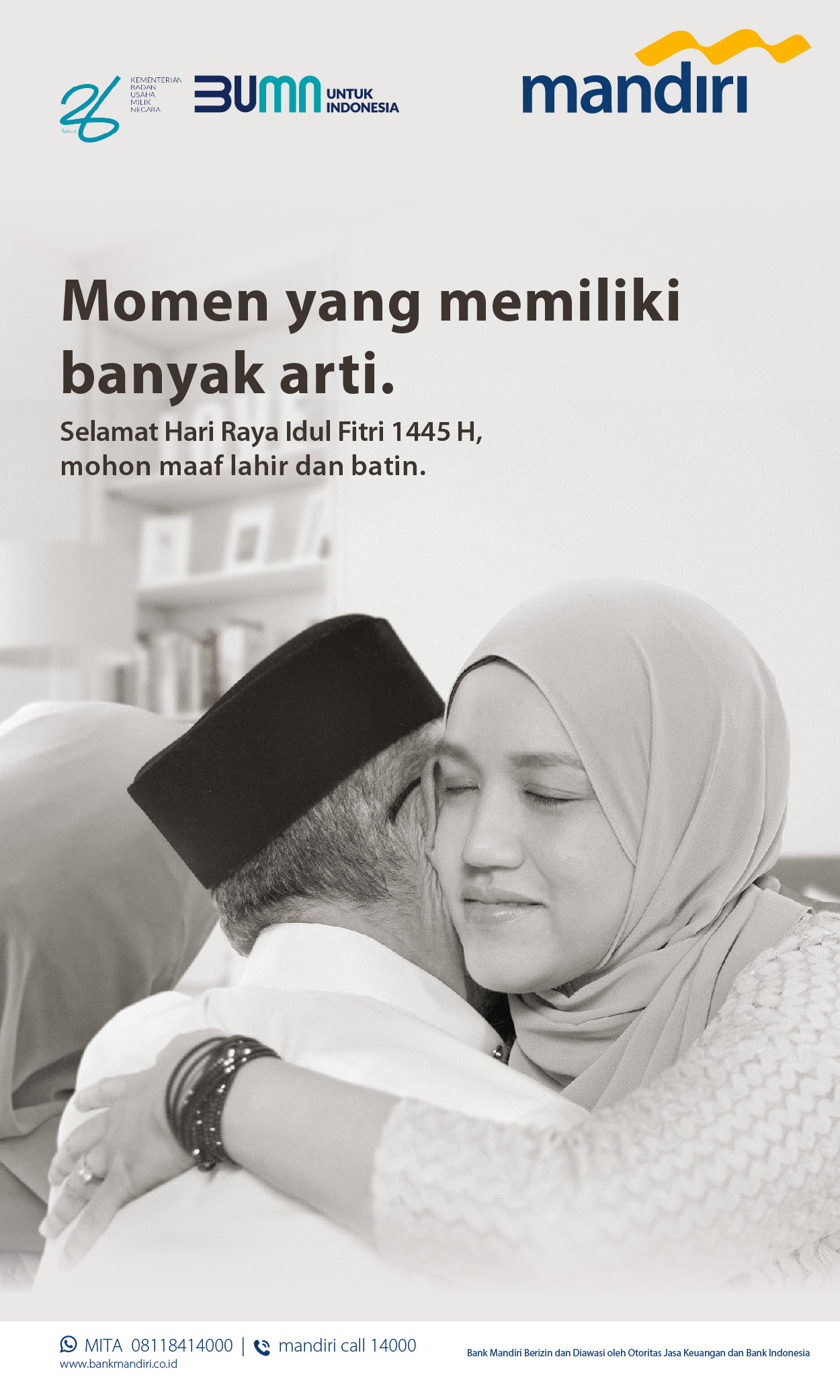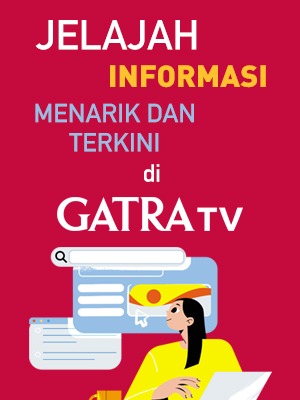Dari investasi lahan, Bob Hasan membangun kerajaan bisnis pertamanya di sektor manufaktur kaca dan kabel. Melobi pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri.
Compang-camping sektor ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Soekarno mulai diperbaiki di era awal Orde Baru. Saat mulai berkuasa, Presiden Soeharto berupaya mengarahkan iklim usaha yang lebih tertata demi akselerasi pembangunan Indonesia.
Ia membentuk Komite Teknis untuk Investasi pada 1967, yang kini bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Soeharto menunjuk Profesor Mohammad Sadli sebagai ketuanya.
Pemerintahan juga baru menyiapkan aturan yang bisa menarik investor. Meski sebenarnya beleid yang mengatur penanaman modal sudah ada di masa pemerintahan Soekarno. Hanya saja, regulasi itu tak efektif menarik minat investor, terutama pemodal asing. Mereka khawatir kebijakan pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1959 terulang.
Mengembalikan kepercayaan investor inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sadli dan wakilnya, Abdoel Raoef Soehoed, yang merupakan sahabat Mohammad Hasan atau Bob Hasan.
Dalam sebuah perbincangan, Hasan meminta masukan Soehoed terkait arah bisnis yang bisa digarap ke depan. Soehoed pun menyarankan agar sang teman mulai berinvestasi dengan membeli tanah. Hal ini karena UU Penanaman Modal segera terbit ketika itu, sehingga bisa memicu investor luar berdatangan dan mencari lokasi strategis untuk membangun usaha. Petuah itu dipatuhi. Hasan pun rajin blusukan mencari lahan dari Bekasi hingga Tangerang. Saat itu, harga tanah di Bekasi sekitar Rp50 per meter persegi.
Informasi yang diberikan AR Soehoed ternyata bertuah. Bakda UU Penanaman Modal terbit, arus modal melesat naik. Banyak perusahaan asing tertarik. Mereka butuh lahan untuk membangun pabrik. Beberapa di antaranya, Australian Consolidated Industry dan Owen Illinois.
Dua perusahaan berbendera Australia dan Amerika Serikat ini, berencana patungan membuat pabrik kaca. Saat itu, Indonesia belum punya produsen kaca. Padahal pasir kuarsa, yang merupakan bahan baku kaca, tersedia melimpah. Mengingat botol obat-obatan kaca banyak paling dicari dan harganya mahal, keduanya sepakat memproduksi botol kaca untuk obat, demi melayani pasar domestik dan ekspor. Saat mencari lahan, pihak perusahaan tertarik membeli tanah Hasan di Bekasi.
Namun, feeling sebagai pebisnis ulung membuat Hasan tak melepas begitu saja asetnya. Dengan cerdik ia menawarkan tanah miliknya sebagai penyertaan modal. Otomatis, ia juga jadi pemilik usaha. "Saya tidak mau hanya menjadi calo tanah," katanya.
Proposal tersebut disetujui Direksi Australian Consolidated Industry dan Owen Illinois. Tanah yang dibeli seharga Rp50 per meter persegi itu, diganti dengan 15% penguasaan saham. Usaha patungan itu dinamai Kanggar, akronim dari dari Kanguru dan Garuda yang menjadi simbol Australia dan Indonesia. Bisnisnya moncer.
Hingga kini, Kanggar masih beroperasi. Meski demikian, nama Hasan tidak lagi terdaftar sebagai pemilik saham. "Saya sudah menjual seluruh saham yang saya miliki. Namun saya tidak pernah bisa melupakan, bahwa itulah salah satu bisnis pertama yang saya miliki," ujarnya.
Kesuksesan pabrik botol meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berbisnis. Ia membeli perusahaan kabel Netherland Cable Fabric milik Phillips, yang sedang merugi. Hal ini karena operasional perusahaan tidak dijalankan secara bersih. Masalah lain, kebijakan impor kabel terlalu longgar, sehingga produk asing membanjiri pasar lokal.
Meski perusahaan itu kurang sehat, dalam hitungan bisnisnya, Hasan menilai bahwa perusahaan yang dikenal dengan Kabelindo itu sebenarnya punya prospek cerah. Indonesia saat itu sedang gencar melakukan pembangunan yang membutuhkan kabel untuk perumahan, industri, hingga jaringan listrik.
Hasan pun manggandeng taipan Julius Tahija untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Akuisisi berjalan mulus dengan nilai penjualan US$5 juta. Agar perusahaan tidak kalah dengan saingan dari luar negeri, ia kembali menemui sahabatnya, AR Soehoed, yang kala itu menjabat Menteri Perindustrian.
Ia juga berbicara dengan Menteri Perhubungan Roesmin Nuryadin, Menteri Pertambangan dan Energi Soebroto, agar membatasi impor kabel dan memprioritaskan produk lokal. Masukan itu diterima. Tak lama, industri kabel Tanah Air bergairah. Kabelindo pun bisa menangguk cuan US$2 juta per tahun.
***
Lobi Hasan ke pemerintah agar bisa membesarkan pengusaha dalam negeri, juga dilakukan di sektor kehutanan. Waktu itu, sekitar akhir dekade 1980-an, Indonesia dikenal sebagai pengekspor kayu. Namun sayangnya, ekspor ini tak banyak berkontribusi bagi perekonomian. Dampak kerusakan hutannya malah lebih terasa.
Pasalnya, ekspor kayu tersebut dalam bentuk gelondongan, yang dihargai US$5 per meter kubik. Kayu hutan melimpah, industri kayu lapis nasional justru sekarat. Padahal, Singapura yang nihil hutan saja, punya 48 pabrik kayu lapis.
Hasan menyarankan, pemerintah melarang ekspor kayu gelondongan agar Indonesia menikmati nilai tambah dari kekayaan hutannya. Namun, ide itu sulit terealisasi karena melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tak kehabisan akal, ia usul agar pemerintah mengenakan instrumen pajak yang tinggi, terutama untuk jenis-jenis kayu primadona.
Kayu jati yang tidak ada tandingannya di dunia, dikenakan pajak ekspor US$1.000 per meter kubik. Kayu eboni dikenakan pajak ekspor US$4.800 per meter kubik. Kayu meranti dari Kalimantan dikenakan pajak ekspor US$500 per meter kubik. Kebijakan tersebut membangkitkan industri kayu lapis nasional. Apalagi, pemerintah membebaskan bea impor produk kayu olahan.
Untuk memperkuat daya saing, Hasan mengajak kawan-kawannya di Asosiasi Pengusaha Kayu Lapis Indonesia (Apkindo) merumuskan sistem pemasaran bersama. Caranya, mengontrol jumlah produksi dan wilayah pemasaran agar Indonesia dapat harga optimal. Langkah ini membuat industri kayu lapis di Singapura, Taiwan, Jepang, Cina, dan Korea Selatan rontok. Mereka pun kehabisan bahan baku. Kalaupun impor dari Indonesia, ongkos pajaknya membuat produk mereka tidak kompetitif dibanding produk Indonesia.
"Setelah tahun 1980-an, Indonesia benar-benar menjadi pemain utama kayu lapis dunia, khususnya untuk kayu tropis. Ekspor kayu lapis Indonesia menguasai 70% produk kayu lapis di dunia. Harga jualnya mencapai US$600 per meter kubik," kata Hasan.
Namun, Hasan tak hanya memikirikan usahanya. Untuk menjaga kelestarian hutan, ia mengusulkan pemerintah menarik Dana Reboisasi dari para pengusaha kehutanan. Pengusaha pun wajib membayar Iuran Hasil Hutan dari jumlah kayu yang mereka ambil di wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pungutannya dihitung dari volume ekspor kayu lapis. Pembayarannya melalui bank, demi meminimalkan kecurangan. "Penghitungan seperti itu lebih akurat, karena jelas ukuran berapa meter kubik kayu yang diperlukan untuk menghasilkan satu meter kubik kayu lapis," katanya.
Langkah Indonesia menuai protes keras negara lain. Mereka menuding Indonesia melakukan kartel. Kampanye hitam terhadap produk kayu Tanah Air mulai disuarakan dengan tudingan merusak kelestarian hutan.
Sebagai Ketua Umum Apkindo, ia diundang oleh Parlemen Uni Eropa untuk menjelaskan soal pengelolaan hutan di Indonesia. Hasan pun menyodorkan bukti bahwa model industrialisasi kehutanan di Indonesia, justru merupakan pengelolaan hutan yang bisa lebih berkelanjutan. "Negara-negara yang menuduh Indonesia merusak hutan, tidak bisa lagi menyalahkan ketika saya tunjukkan fakta-fakta sebenarnya," katanya.
Putri Kartika Utami



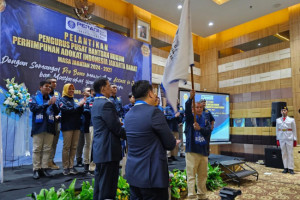

_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)