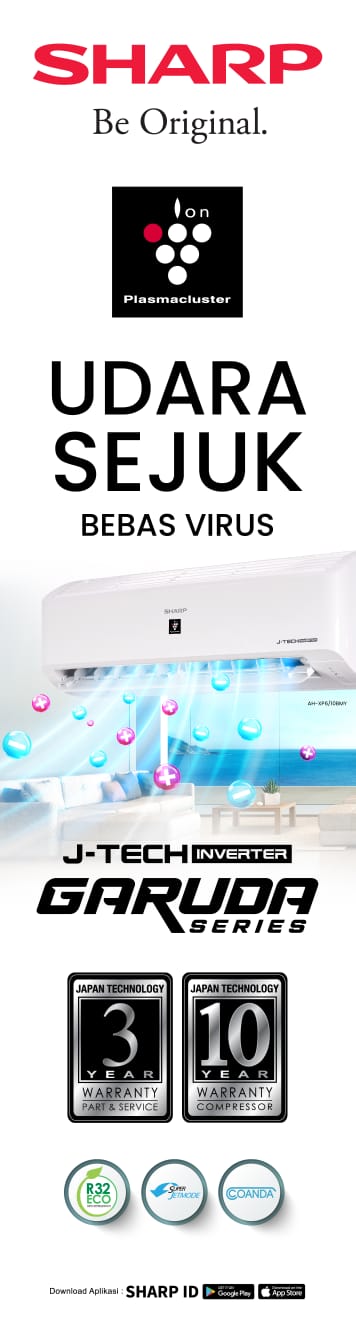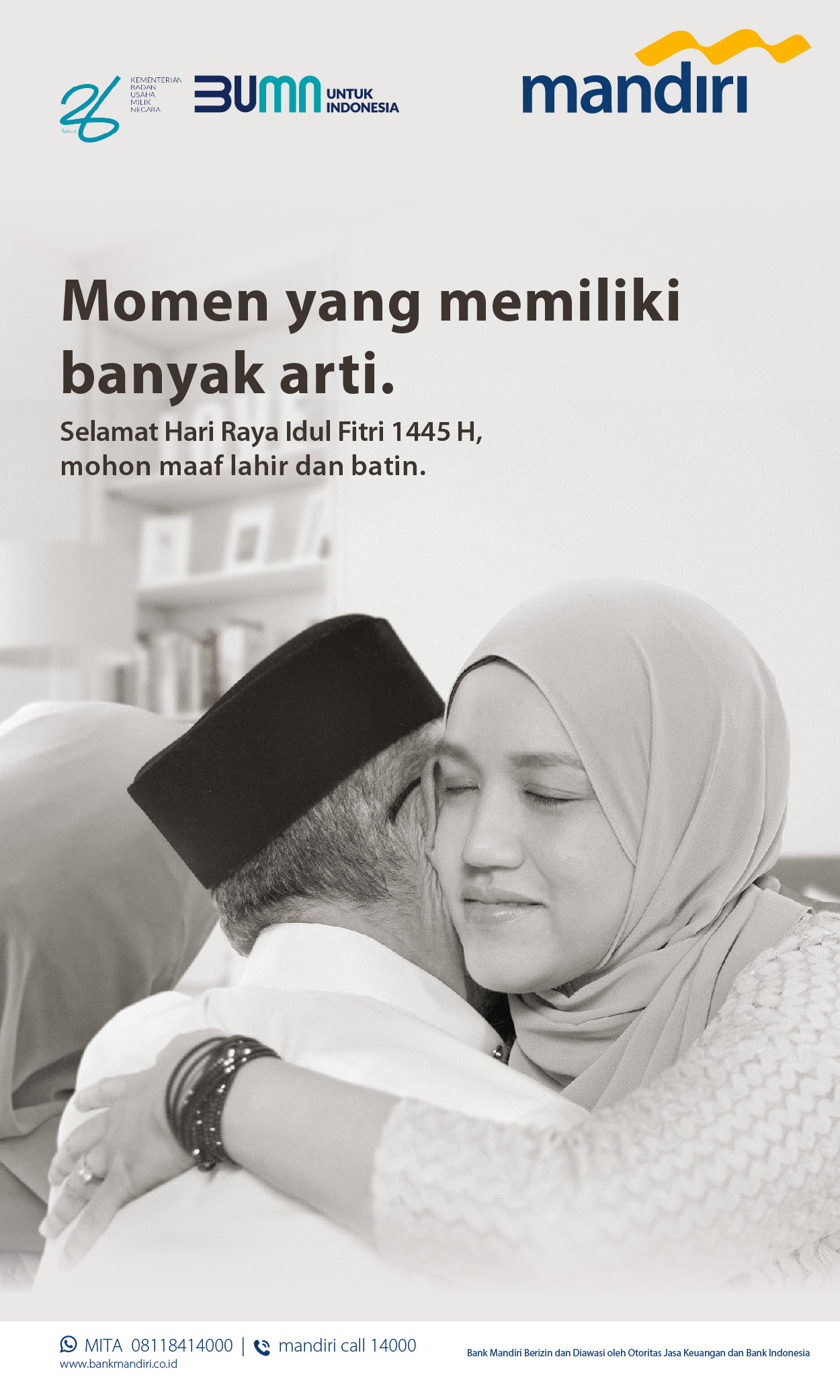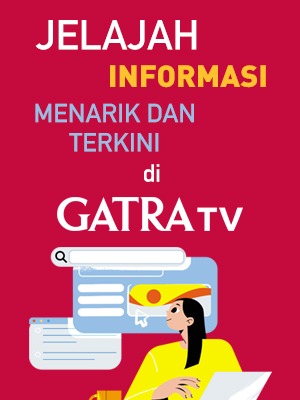Gerakan pro demokrasi berkembang lewat forum diskusi dan memperbanyak keterlibatan sipil di pemerintahan. Krisis ekonomi Indonesia makin parah setelah kehadiran IMF. Sejumlah menteri menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap Soeharto.
Sepanjang 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 8%. Hal ini membuat investor menaruh perhatian, sehingga arus modal mengalir deras ke Indonesia. Bersama negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Thailand, kemajuan yang dicapai bahkan disebut sebagai "Keajaiban Ekonomi Asia".
"Kemajuan Indonesia di satu sisi dianggap sebagai sebuah keberhasilan, karena meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain dianggap sebagai ancaman, karena dengan kekuatan ekonomi yang besar dan pasar yang juga besar, Indonesia akan bisa menjadi pemain utama dunia," demikian tulis Bob Hasan dalam bukunya, Founding Fathers dan Aku (Gatra Pustaka, 2020).
Di sisi lain, gerakan pro demokrasi mulai memasuki Asia sejak pertengahan 1980-an. Beberapa pemerintahan yang dianggap otoriter, mendapat perlawanan dari rakyatnya. Gerakan pro demokrasi mendapat angin segar dengan kemunculan Megawati Soekarnoputri di ajang politik. Pada 1987, Megawati berhasil diajak Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, Soerjadi, untuk bergabung dalam partai. "Pak Harto bukan tidak membaca perubahan arah politik besar yang sedang terjadi. Ia menyadari bahwa Indonesia pun harus bergerak ke arah demokrasi," tulis Hasan.
Untuk merespons perubahan itu, dipilihlah Ketua Umum Golkar yang bukan dari kalangan militer, yakni Menteri Penerangan Harmoko. Belakangan, ketika terpilih menjadi Presiden RI periode keenam pada Maret 1998, kursi wakil presiden dipercayakan pada Prof. BJ Habibie. Demikian pula dengan kabinet, yang untuk pertama kalinya ada tiga menteri berlatar belakang pengusaha, termasuk Hasan yang diserahi jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Semua kemajuan ekonomi terusik ketika di awal Juli 1997 terjadi gejolak keuangan di Thailand. Keterbatasan cadangan devisa yang dimiliki Bank Sentral Thailand memaksa mereka melepas kebijakan nilai tukar tetap mereka. Dilepaskannya nilai tukar baht ke pasar bebas, membuat mata uang Thailand terjun bebas. Tingginya utang luar negeri membuat Thailand secara finansial sudah berada dalam kebangkrutan.
Di sisi lain, AS yang baru pulih dari resesi sejak 1990, mencoba mempercepat pemulihan perekonomian mereka. Bank sentral AS menurunkan tingkat suku bunga, sehingga membuat para investor cepat menarik investasinya di Asia untuk dipindahkan ke AS.
Penarikan modal yang cepat oleh para investor secara bersamaan, memperburuk keadaan. Tiba-tiba saja terjadi kelangkaan dolar di negara-negara Asia, sehingga menekan nilai tukar semua mata uang Asia. Rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, tiba-tiba melonjak di atas 160%.
Indonesia sendiri sebenarnya dalam kondisi baik ketika krisis keuangan melanda Thailand. Tingkat inflasi berada di bawah 4%. Surplus perdagangan tercatat masih sekitar US$900 juta. Cadangan devisa sekitar US$20 miliar.
Dengan kondisi seperti itu, sebenarnya Indonesia masih jauh dari krisis. Apalagi untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi, Bank Indonesia memperlebar rentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. BI menaikan rentang dari semula 8% menjadi 12%.
Tak disangka, langkah BI justru menambah ketidakpercayaan pasar. "Terasa ada pihak yang mencoba mengail di air keruh. Mereka ingin memanfaatkan krisis keuangan yang terjadi untuk sekaligus menggoyahkan kondisi politik dalam negeri," tulis Hasan.
Pada 14 Agustus 1997, BI mencabut kebijakan nilai tukar yang mengambang menjadi nilai tukar bebas. Ini membuat tekanan terhadap rupiah makin menjadi-jadi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sebelumnya pada kisaran Rp2.000, terpuruk sampai Rp17.000.
***
Dalam kondisi tidak menentu, pemerintah memutuskan meminta dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Keputusan itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan letter of intent antara Soeharto dan Direktur Eksekutif IMF, Michael Camdesus, pada Sidang Kabinet Oktober 1997. Suntikan dana US$30 miliar tersebut tentu saja bersyarat.
Restrukturisasi yang diminta IMF membuat pemerintah harus menutup 16 bank yang tidak solvent pada 16 November 1997. Ini membuat masyarakat menarik uang secara gila-gilaan dari bank. Belum lagi, pemerintah Indonesia diwajibkan menaikkan suku bunga. Tentu saja semua faktor itu membuat krisis ekonomi makin dalam.
"Saya sempat mengusulkan kepada Pak Harto untuk mengundang ahli moneter dari Amerika Serikat, Steve Hanke, dan mendengarkan konsepnya dalam meredam nilai tukar. Profesor Ekonomi dari Johns Hopkins University ini, saya tahu mengembangkan currency board system. Konsepnya itu bisa berjalan baik di negara-negara Eropa Timur seperti Bulgaria," Hasan memaparkan.
Awalnya, Soeharto sepakat dengan ide ini. Namun, belakangan Presiden AS kala itu, Bill Clinton, mengutus mantan Wakil Presiden AS, Walter Mondale, bertemu Soeharto agar tidak menerapkan currency board system. Akhirnya, Soeharto tak pernah memberlakukan sistem tersebut.
Harga terhadap keputusan itu harus dibayar mahal. Krisis keuangan 1997 berlanjut hingga Mei 1998, sehingga menimbulkan krisis multidimensi yang memancing kerusuhan di banyak kota di Indonesia.
Dalam kondisi yang makin tidak menentu, pada 19 Mei 1998, Soeharto memanggil Hasan ke Cendana pada malam hari. Ternyata di sana sudah ada Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Ginandjar Kartasasmita. Kepada keduanya, Soeharto mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Indonesia mengalami kemunduran. Apalagi kalau sampai terjadi pertumpahan darah, karena pada 20 Mei, Amien Rais berencana mengerahkan massa datang ke Istana Merdeka.
"Saya tidak ingin sampai terjadi pertumpahan darah hanya karena perebutan kekuasaan. Lebih baik saya yang menjadi korban daripada para mahasiswa," kata Soeharto, demikian tulis Hasan.
Hasan lantas menanggapi pernyataan itu. "Kalau Pak Harto mundur sebagai Presiden, saya juga mundur sebagai menteri," ucapnya kala itu.
Keesokan harinya, kabinet mengadakan rapat di Gedung Bappenas. Menko Ekuin mengundang seluruh menteri untuk menyampaikan hasil pertemuannya dengan Soeharto. Namun ternyata pertemuan itu bukan untuk memutuskan langkah yang akan dilakukan atas rencana pengunduran diri Presiden, melainkan menggalang tanda tangan menyatakan mosi tidak percaya kepada Soeharto dan menyatakan sikap tidak mau lagi bekerja sama.
"Oleh karena itu, saya tidak pernah mau ikut menandatangani surat pernyataan para menteri itu. Saya langsung meninggalkan Gedung Bappenas. Ada tiga menteri, termasuk saya yang tidak mau ikut menandatangani surat pernyataan tersebut," tulis Hasan lagi.
Berbagai aksi demonstrasi memaksa Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dan posisinya digantikan BJ Habibie.
Flora Libra Yanti



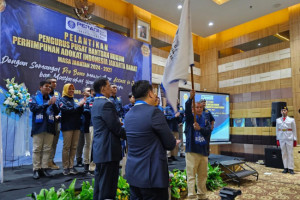

_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)