
Maraknya perangkat pintar malah membuat anak-anak dan remaja kecanduan internet. Memicu gangguan jiwa hingga merusak masa depan. Perlu penanganan yang tepat.
Ada yang berbeda dengan rumah sakit jiwa zaman sekarang. Bukan hanya orang dewasa, belakangan banyak anak-anak dan remaja yang berobat di sana. Tidak sedikit dari mereka yang harus dirawat inap. “Ada anak SMP dan SMA. Kebanyakan pasien kecanduan gadget,” kata Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dr. Aliyah Himawati, saat ditanya Novita Rahmwati dari GATRA Selasa pekan lalu.
Menurut Aliyah, di institusinya sudah ada tiga pasien remaja yang dirawat inap. Salah satu pasien yang ditangani adalah seorang lulusan SMA, sebut saja Ani. Ia sudah dua pekan dirawat, dan hendak pulang. Gadis 18 tahun ini kecanduan melihat video K-pop di aplikasi media sosial YouTube.
Ia dibawa ke RS karena tak mau makan dan mandi. Bahkan saat mendapat pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan, kadar hemoglobinnya rendah. Parahnya, beberapa pekan lalu, Ani tidak keluar kamar selama sepekan, tak mau makan hingga kesehatan fisiknya terganggu.
Yang membuat kondisnya tambah buruk, keseharian Ani tidak terpantau orangtuanya. Kedua orangtuanya pekerja pabrik dengan sistem kerja shift.
Setelah lulus sekolah pada Juli lalu, Ani tak memiliki kegiatan lainn. Juga tak punya motivasi melanjutkan studinya. “Akhirnya selama empat bulan gadis ini hanya menonton YouTube setiap hari,” Aliyah menambahkan.
Di rumah sakit, ia diberi terapi perilaku dan obat pengendalian emosi. Pasca-rawat inap, gadis ini mendapatkan pendampingan selama enam bulan. Setelah konsultasi, Ani sudah membaik. Ani berniat les bahasa Inggris dan Korea, serta berencana kursus desain. “Kami rasa les bahasa Korea positif bagi anak ini,” tutur Aliyah.
Tak hanya di Solo, korban adiksi internet (AI), terutama permainan daring atau game online, banyak dijumpai di beberapa RS daerah lain. RS di Cisarua, Jawa Barat, misalnya, pernah menangani 250 pasien game online. Begitu pula RS Jiwa Provinsi Jawa Barat di Bandung mencatat 205 pasien anak-remaja yang diterapi sejak 2016.
Heboh AI terungkap lagi setelah dokter Kristiana Siste melakukan riset di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Disertasi yang membawanya meraih gelar doktor itu didapat dalam promosinya di Gedung IMERI FKUI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa pekan lalu.
Siste mengemukakan 31,1% remaja di DKI Jakarta mengalami kecanduan alias adiksi internet. Ini seiring dengan meningkatnya penggunaan telepon pintar.
Persentase sebesar itu tentu mengkhawatirkan. Ini lantaran persentase AI di dunia hanya berkisar 4,5% hingga 19,1% pada remaja, dan 0,7%-18,3% pada orang dewasa. Prevalensi adiksi di Asia diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan di Eropa atau Amerika.
Menurut hasil studi Cecilia Cheng, psikolog pada Universitas Hong Kong, prevalensi kecanduan internet di dunia rata-rata 6% tanpa melihat usia. Itu diperoleh dari hasil studinya terhadap 31 negara.
Negara Timur Tengah menempati urutan pertama adiksinya dengan angka 10,9%, disusul Amerika Utara 8,0%, dan Asia, 7,1% (lihat infografis). “Pertanyaannya, seberapa gawat? Jadi karena angkanya juga cukup bermakna, ini menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani segera,” kata Kepala Departemen Medik Kesehatan Jiwa RSCM-FKUI tersebut kepada wartawan GATRA Syah Deva Ammurabi, Selasa lalu.
Tingginya angka tersebut karena para remaja Asia lebih sulit berekspresi di lingkungannya, sehingga lebih memilih berekspresi di dunia maya. Ini jelas akan membahayakan kejiwaan anak tersebut.
Dampak kejiwaan AI menjadi perhatian Siste. Ia berinisiatif mengembangkan metode deteksi dini dengan pengukuran KDAI (kuesioner diagnostik adiksi internet). Untuk mengonfirmasi hasil KDAI, ia menggunakan resting state fMRI atau rsfMRI BOLD (sejenis magnetic resonance imaging untuk memindai jaringan saraf di otak).
Dengan neuro-imaging ini, peneliti bisa melihat ada tidaknya gangguan di otak, terutama di areal dorsolateral prefrontal cortex yang berkaitan dengan fungsi kognitif, motivasi dan pengendalian rangsangan seseorang yang dipindai.
Sebanyak 643 responden berumur 10-20 tahun di Jakarta diteliti. Mereka tersebar di empat SMP dan lima SMA di Ibu Kota. Mereka dipantau selama setahun. Sebagian besar remaja itu menggunakan internet di rumah (91,2%).
Adapun penggunaannya lebih dari 20 jam per pekan. Mereka umumnya juga memanfaatkan internet untuk membuka media sosial (53,3%), mencari edukasi (20,8%), dan bermain game online atau permainan daring (17,0%).
Setelah diteliti ada kaitan antara skor KDAI dengan fungsi jaringan otak yang dipindai dengan rsfMRI. Semakin tinggi skor KDAI hubungan antara jaringan otak yang mencegah adiksi semakin lemah.
Itu bisa dilihat dari skor temperamen mereka, yang ditinjau dari segi novelty seeking (NS), harm avoidance (HA), dan reward dependence (RD). NS adalah sifat kepribadian yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi di otak. Sedangkan HA merupakan sifat kepribadian yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan, pesimisme, perasaan malu, menjadi takut, ragu-ragu, dan mudah lelah. Sementara itu, RD adalah sifat kepribadian yang berhubungan dengan ambisi, hangat, sentimental, menyenangkan, mudah bergaul, peka, simpatik, dan bergantung secara sosial.
Dari situ ketahuan, remaja laki-laki yang kecanduan internet bertemperamen NS yang lebih tinggi. Sebaliknya, remaja perempuan adiksi justru lebih tinggi pada temperamen jenis HA dan RD. “Selanjutnya, laki-laki cenderung memiliki masalah perilaku, sedangkan perempuan lebih kepada masalah emosi,” kata Siste dalam ringkasan disertasinya.
Maka, Siste memandang deteksi dini dengan KDAI penting untuk menentukan langkah intervensi yang tepat, apakah diperlukan upaya kuratif (penyembuhan) atau preventif (pencegahan). “Sehingga tidak terjadi diagnosis berlebihan,” katanya. Ia juga meminta pemerintah lebih memperhatikan masalah ini.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Anung Sugihantono, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun pedoman pencegahan dan pengendalian ketergantungan pornografi, serta permainan berbasis internet (online) pada 2017. “Ini juga telah disosialisasikan di beberapa provinsi, khususnya di DKI Jakarta,” katanya kepada Ryan Sara Pratiwi dari GATRA.
Studi Siste bakal menjadi modul terapi untuk adiksi internet sehingga bisa menjadi kebijakan nasional, mengingat saat ini belum ada bentuk terapi nasional untuk adiksi internet.
Sementara itu, psikiater anak dan remaja di Grha Atma Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas, dokter Lina Budiyanti, mengatakan bahwa pada umumnya kecanduan gawai terjadi sejak perkembangan teknologi dan internet bisa diakses dengan mudah.
Pada 2015, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition (DSM-5) sudah memberikan tanda untuk memisahkan gaming addiction dan internet addiction menjadi diagnosis tersendiri. “Lalu WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) baru memisahkan diagnosis gaming addiction atau internet addiction sejak 2018,” katanya kepada Mega Dwi Anggraeni dari GATRA.
Lebih lanjut Lina mengatakan, pada umumnya tidak semua internet dan game berpotensi menjadi candu. Faktor internal dan eksternal, kata Lina, bisa mempengaruhi seseorang kecanduan terhadap gawai.
Lina mencontohkan, seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri biasanya berpotensi kecanduan terhadap gawai. “Selain itu, pola asuh juga bisa memengaruhi seseorang untuk menjadi kecanduan gawai,” ujar Lina.
Bukan itu saja, mengutip beberapa jurnal yang menjadi acunnya, game online juga berpotensi menjadi candu jika dibandingkan game offline. Salah satunya adalah shooting game.



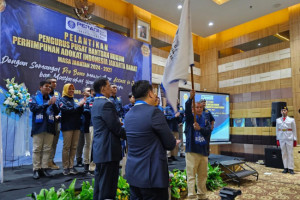

_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)















